SUSTAINABLE DEVELOPMENT; ANTARA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA
Oleh: Hafidh Fadhlurrohman
PENGANTAR/PENDAHULUAN
Pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu hal yang baru, baik ketika
ditinjau dari sudut pandang nasional maupun global. Dan konsep itu hadir dalam
upaya menjadi solusi untuk pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
lingkungan, serta upaya untuk menyerasikan kedua hal tersebut dalam
pembangunan. Tapi selanjutnya bahwa fakta yang terjadi dalam pelaksanaannya,
konsep pembangunan berkelanjutan belum dipahami secara baik dan merata yang
pada akhirnya mengakibatkan masih kentara akan kerancuan pada tingkat kebijakan
dan pengaturan, terutama pada tingkat implementasinya. Selanjutnya Suardi
(2004) menjelaskan pengertian dari konsep pembangunan berkelanjutan, menurutnya
konsep tersebut mengandung pengertian sebagai pembangunan yang memperhatikan
dan mempertimbangkan dimensi lingkungan. Pun ia mengutip dari Undang-undang No.
32 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya
sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi
ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan
yang akan datang.
Pembangunan berkelanjutan yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan
dengan memperhatikan faktor lingkungan merupakan suatu hal yang selaras dengan
keinginan PBB untuk menanggulangi kerusakan lingkungan yang terjadi (Suardi,
2014). Kerusakan lingkungan terjadi akibat prilaku manusia yang kapitalistik
dan konsumtif yang tinggi sehingga mendorong untuk memiliki nafsu serakah
terhadap sumber daya alam yang tersedia tanpa mempertimbangkan aspek
keselamatan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Dan Suardi (2014)
menjelaskan bahwa ada kekeliruan pemahaman dari manusia yang menganggap bahwa
sumber daya alam yang tersedia adalah bahan materi yang harus dieksploitasi
untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan manusia yang konsumtif. Oleh karena itu,
banyak sumber daya alam yang dieksploitasi fungsinya hanya sekedar untuk
memenuhi kebutuhan untuk makan, air, perumahan dan sumber lainnya tanpa
merencakanan solusi atas pencemaran lingkungan tersebut.
Kalau dilihat penjelasan yang dipaparkan oleh Suardi (2014) ada suatu
dilema terkait dinamika pembangunan, di satu sisi pembangunan negara diharapkan
memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan hidup masyarakatnya,
tetapi pada sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap ,merosotnya kualitas
lingkungan hidup secara permanen dalam jangka panjang. Sehingga dalam
penjelasannya Suardi memberikan studi kasus dengan data yang mengatakan bahwa
kondisi lingkungan hidup di Indonesia sangat buruk yang pada akhirnya
menyebabkan bencana alam di berbagai wilayah.
Selanjutnya Suardi menggambarkan bahwa ada suatu perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan industri yang membawa berbagai kemajuan bagi
peradaban manusia, tetapi hal tersebut sekaligus mewujudkan risiko-risiko dalam
kehidupan manusia dan lingkungannya. Bisa kita lihat dari fenomena pencemaran
lingkungan hidup akibat buang air limbah industri yang mengancam eksistensi
kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam jangka panjang, walaupun kita akui
bahwa kegiatan sektor industri meningkatkan sektor perekonomian masyarakat.
Artinya, dalam fenomena di atas menggambarkan bahwa pola kebijakan
pembangunan yang hanya berorientasi pada ekonomi pada pengelolaan sumber daya
alam, akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa pada
gilirannya akan merugikan manusia.
Paradigma pembangunan seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi dan harus
diubah, karena pembangunan seperti itu walaupun memberikan keuntungan ekonomi,
tetapi juga akan menimbulkan perubahan-perubahan terhadap lingkungan fisik dan
sosial budaya yang memerlukan pengamanan secukupnya agar tidak merugikan dalam
jangka panjang.
Menelaah lebih jauh dari problematika yang telah dijelaskan, selanjutnya
Suardi menunjukan bahwa secara harfiah baik pengingkatan kualitas kesejahteraan
hidup masyarakat maupun tindakan untuk mencegah merosotnya kualitas lingkungan
hidup adalah keduanya merupakan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak
konstitusional warga negaranya di bidang hak asasi manusia, yang argumentasi
Suardi ini merujuk pada Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945. Ada suatu problrmatika
antara eksploitasi lingkungan yang menyebabkan merosotnya kualitas lingkungan
hidup sehingga tidak berfungsi sebagai sistem pendukung kehidupan dan di sisi
lain peningkatan kesejahteraan manusia adalah mutlak. Pada akhirnya lingkungan
yang menjadi sumber materil tidak bisa terhindar dari eksplorasi dan
eksploitasi yang berimplikasi terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan,
yang hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
PEMBAHASAN
Pergeseran Millenium Development Menjadi
Sustainable Development
Hari ini kita semua telah mengetahui bahwa dalam pembangunan ada
pergeseran, yang dulu pembangunan basisnya adalah MDGs (Millenium Development
Goals), kini pembangunan berubah menjadi berbasis SDGs (Sustainable
Development Goals). Perlu kita fahami terlebih dahulu, hal tersebut bisa
terjadi karena ada permasalahan-permasalahan yang tidak terselesaikan melalui
konsep Agenda Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals),
sehingga terjadinya pergeseran atau perubahan konsep.
Agenda Pembangunan Millenium atau Millenium Development Goals
merupakan sebuah kebijakan dan langkah global dalam menjalankan pembangunan
yang tertuang dalam piagam yang disepakati oleh PBB pada tahun 1992. Dalam MDGs
ada delapan poin yang menjadi tujuan untuk mengatasi tantangan pembangunan di
era global, diantaranya: 1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, 2) mencapai
pendidikan dasar untuk semua, 3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan, 4) menurunkan angka kematian anak, 5) meningkatkan kesehatan ibu, 6)
memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, 7) memastikan
kelestarian lingkungan hidup, 8) mengembangkan kemitraan global untuk
pembangunan.
Tujuan-tujuan di atas diharapkan dapat menjadi solusi dan pertumbungan
negara dalam kurun waktu 15 tahun. Setelah konsep pembangunan tersebut
berjalan, MDGs telah diagungkan dan dinobatkan sebagai agenda pembangunan
global yang sukses. Setelah penulis membaca beberapa jurnal ilmiah terkait
pembangunan, khususnya yang membahas terkait MDGs dan SDGs. Dalam beberapa
pendapat disebutkan dalam hal ini PBB menyebutkan bahwa MDGs merupakan sebuah
gerakan anti kemiskinan paling sukses. Ia mampu mencapai target-target dengan
baik setiap tahunnya.
Namun sayangnya, agenda pembangunan tersebut belum mendapat predikat
sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu aspek yang menjadi indikator
pembangunan bisa dibilang berkelanjutan adalah pembangunan yang mencakup
dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang holistik dan dijalankan dengan cara
yang seimbang. Walaupun aspek ekonomi sudah ada di konsep MDGs, namun dua hal
selanjutnya tidak terlalu menjadi perhatian dan prioritas.
Hal tersebut membuat para pemimpin negara merumuskan ulang konsep
pembangunan, maka dalam konferensi PBB hasil rumusan dengan berbagai negara
pembicaraan mengenai pembangunan ialah konsep pembangunan yang berkelanjutan
atau sering kita dengar dengan istilah SDGs (Sustainable Development Goals).
Pembangunan berkelanjutan menjadi konsep yang sangat penting dalam
pelaksanaan SDGs. Pembangunan berkelanjutan menjadi suatu upaya bersama yang
memiliki tujuan dalam membangun masa depan yang inklusif dan tangguh. Agar
tujuan pembangunan tercapai, maka harus bisa memformulasikan tiga elemen, yakni
pertumbuhan ekonomi, tatanan sosial yag inklusif dan perlindungan terhadap
lingkungan.
Dari analisa di atas, saya memiliki hipotesis bahwa yang menjadi persoalan
dalam pembangunan sekarang adalah tidak meratanya dimensi ekonomi dan sosial,
yang kedua kurangnya perlindungan terhadap lingkungan.
Artinya, permasalahan dalam pembangunan adalah kurang nya kesetaraan gender
yang dilibatkan, sehingga berakibat pada kesejahteraan gender. Tidak adanya
kesetaraan gender dalam pembangunan juga mengakibatkan kurang maksimalnya aspek
pemberdayaan sosial. Sehingga pembangunan tidak terasa secara maksimal
dampaknya oleh masyarakat. Maka dalam hal ini, SDGs berupaya untuk menuntaskan
masalah tersebut. sehingga output pembangunan itu bisa berdampak secara
maksimal terhadap masyarakat.
Selanjutnya, perlindungan terhadap lingkungan pun menjadi suatu
permasalahan karena dalam MDGs tidak menjadi prioritas utama. Sehingga
pembangunan berdampak buruk terhadap lingkungan, yang mengakibatkan pada
pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan sehingga terjadi perubahan iklim
yang akan mempengaruhi terhadap kesehatan masyarakat.
Sehingga SDGs berupaya untuk menajadi solusi terhadap dimensi lingkungan.
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan linngkungan menjadi fokus utama dalam
SDGs. Pun dalam hal ini mendapat perhatian khusus bagi negara-negara anggota
PBB. Permasalahan lingkungan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap
kehidupan manusia. Karena perubahan iklim sudah berdampak pada kesehatan
manusia, keamanan pangan dan air, migrasi, perdamaian dan keamanan.
Kita mempunyai kesimpulan bahwa dalam dimensi internasional pun dua
permasalahan tadi menjadi sorotan utama, dan fokus pembangunan dunia tujuannya
adalah keberlanjutan yang mencakup aspek sosial ekonomi dan perlindungan
lingkungan.
Pengertian dan Urgensi Prinsip Sustainable
Development dalam Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Lingkungan
Istilah “keberlanjutan” dewasa ini telah menjadi buzzword di segala
aktivitas pembangunan. Keberlanjutan diperlukan untuk terciptanya keseimbangan
antara alam dan manusia, pembangunan yang mengabaikan keterkaitan keduanya
terbukti menimbulkan biaya yang mahal yang pada akhirnya berimplikasi pada penurunan
kesejahteraan manusia.
Suardi (2014) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan diperkenalkan
dalam World Conservation Strategy (Strategi Konservasi Dunia) pada 1980.
Ia merupakan reaksi ketidakpuasan atas penanganan lingkungan selama ini. Salah
satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah
bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan
pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.
Selanjutnya pembangunan berkelanjutan sesuai dengan laporan yang
dikeluarkan oleh Commision PBB dirumuskan sebagai pembangunan yang
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengabaikan hak generasi
mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Suardi, 2014). Selanutnya Suardi
(2014) mengutip pendapat Otto Sumarwoto, yang menjelaskan bahwa faktor
lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan
adalah: Pertama, terpeliharanya proses ekologi yang esensial. Kedua,
tersedianya sumber daya yang cukup. Ketiga, lingkungan sosial budaya dan
ekonomi yang sesuai. Sehingga ketiga klasifikasi yang dijelaskan Otto tersebut
bisa didefinisikan sebagai perubahan positif sosial ekonomi yang tidak
mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung kepadanya.
(Suardi, 2014). Keberhasilan akan perubahan positif tersebut harus dibekali
dengan pematangan perencanaan, kebijakan, dan proses pembelajaran sosial yang
terpadu, serta harus bisa menjangkau masyarakat sehingga negara tidak berdiri
sendiri tapi melibatkan lembaga masyarakat yang ada di bawah, dunia usaha, yang
keduanya dijangkau melalui pemerintahan negara.
Suardi (2014) menjelaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan meluas
dari definisi yang sebelumnya merupakan isu lingkungan menjadi berbagai isu
pembangunan yang saling bersifat komplementer. Dokumen PBB dalam World
Summit tahun 2005 menyatakan pembangunan berkelanjutan terdiri atas tiga
pilar yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan
yang ketiganya saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Karena ketiganya
saling berkaitan dan menimbulkan sebab akibat, maka ketiga hal tersebut tidak
bisa dipisahkan.
Kemudian ada tolak ukur yang dituturkan oleh Otto (2006) untuk pembangunan
berkelanjutan secara sederhana terkait pembangunan pemerintah untuk menilai
keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Menurutnya ada 6 tolak ukur,
yakni: pro lingkungan hidup, pro rakyat miskin, pro kesetaraan gender, pro penciptaan
lapangan pekerjaan, pro dengan bentuk kesatuan RI, dan harus anti KKN (Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme).
Hal ini senada dengan konstitusi negara terkait asa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang memiliki poin tentang
kelestarian dan keberlanjutan yang memiliki arti bahwa setiap orang memikul
kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya
dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem
dan memperbaiki lingkungan hidup.
Prof Oekan (2017) dalam bukunya yang berjudul Ekologi Manusia dan
Pembangunan Berkelanjutan mengatakan bahwa salah satu permasalahan lingkungan
yang kita hadapi saat ini adalah cara kita memperlakukan lingkungan, atau lebih
tepatnya cara kita menempatkan lingkungan dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan. Kita mesti sadar bahwa
hidupnya ratusan juta manusia di Indonesia dominasinya di pulau-pulau dan
perairan Indonesia. Kita membutuhkan pembangunan yang menyeimbangkan antara
peningkatan kesejahteraan dengan pengelolaan lingkungan hidup karan hal
tersebut dalam upaya untuk meningkatkan kemakmuran, menyediakan lahan hidup dan
permukiman serta memajukan pertumbuhan ekonomi.
Prinsip Sustainable Development dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia
Suardi (2014) menjelaskan bahwa HAM telah hadir sejak lama, namun ia masih
relevan dan aktual dari waktu ke waktu sejak manusia hadir di dunia sampai saat
sekarang ini. Dia aktual secara terus menerus baik dalam keilmuan, politik
maupun hukum. Yang pada akhirnya menyebabkan perkembangan dalam bentuk,
pemahaman dan teori. HAM dikatakan aktual dan berkembang bisa dibuktikan dengan
lahirnya HAM generasi III, yaitu hak atas pembangunan, di samping Sipil and
Political Right pada generasi I dan hak ekonomi, sosial dan budaya pada
generasi ke II.
Karena dalam pengertian dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan itu
memiliki aspek manusia dan lingkungan, pada akhirnya hak-hak asasi manusia
memperoleh konteksnya yang baru dalam hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan
serta pembangunan yang berpusat pada manusia. Keterkaitan yang esensial antara
hak asasi manusia dengan lingkungan, pembangunan dan perdamaian yang kemudian
dikembangkan oleh para pemangku kebijakan, pemerhati politik, aktivis HAM,
pakar dan pekerja pembangunan. Sehingga terjadi perkembangn mengenai diskursus
hak asasi manusia terhadap pembangunan, penerapan dan implementasinya, serta
sosio kultur yang ada di masyarakat. (Suardi, 2014)
Pada dasarnya manusia memiliki derajat dan martabat yang sama dengan
demikian hak-hak dan kewajiban pun sama. Pandangan ini memberikan dasar
pemikiran tenatng pengertian HAM itu sendiri, yang Suardi (2014) menjelaskannya
sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib
dihormati, dijungjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia. Prinsip dasar hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, artinya dengan
kehidupanlah manusia dapat melaksanakan tugasnya dan memenuhi kebutuhannya.
Dalam penjelasan terkahir pada bagian ini Suardi (2014) mengatakan bahwa
konstruksi HAM dalam konteks sustainable development tersebut mengindikasikan
bahwa pengembangan diri manusia serta keberlangsungannya sangat ditentukan oleh
keadaan lingkungan yang sustainable sepanjang manusia ada di alam ini. Dengan
demikian prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan bagian yang tidak dapat
dipisahkan dengan prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Hakikat pembangunan
berkelanjutan adalah untuk mendukung keberlangsungan Hak Asasi Manusia itu
sendiri.
Problematika Penerapan Sustainable
Development dalam Pengelolaan Lingkungan dan Implikasinya terhadap
Pemenuhan HAM
Pembangunan yang menjadikan sumber daya alam yang bersifat terbatas sebagai
penopang utamanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak
terbatas demi kesejahteraan manusia. Akhirnya menimbulkan kesenjangan atas
pelaksanaan pembangunan yang tidak ekologis, terlihat antara pertumbuhan laju
penduduk yang sangat cepat dengan merosotnya kualitas lingkungan hidup yang
ditandai dengan tercemarnya berbagai sumber daya alam dan terjadinya bencana di
mana-mana.
Pemerosotan kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh semakin banyaknya
produksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Hal ini
selaras dengan tawaran Robert Malthus yang dikutip oleh Suardi (2014) yang
mengatakan bahwa untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk dan kebutuhan
pangan maka mau tidak mau harus meningkatkan produktivitas pangan. Yang kita
ketahui semua bahwa produksi pangan tersebut berasal dari sumber daya alam yang
bersifat terbatas, tentu ketika produktivitas meningkat artinya ekspolitasi
alam pun semakin meningkat sehingga akibat yang timbul kemudian adalah proses
degradasi lingkungan dan pencemaran lingkungan yang semakin menjadi-jadi dan
bertambah parah.
Untuk mengatasi persoalan di atas, menurut Syaiful Bahri yang kemudian
dikutip oleh Suardi (2014) tanggung jawab manusia untuk menjaga lingkungan
hidup dapat dilihat dari 3 sudut pandang, diantaranya lingkungan hidup dari
sudut pandng religius, sudut pandang humanism, serta sudut pandang etika dan
moral. Selanjutnya suardi memiliki pandangan bahwa tanggung jawab manusia untuk
menjaga lingkungan agar tetap lestari berimplikasi terhadap hak asasi manusia
itu sendiri, karena antara lingkungan dan manusia saling berkaitan dan
ketergantungan.
Ketika pengetahuan dan sudut pandang yang telah dijelaskan di atas menjadi
tawaran bagi manusia, terkadang manusia belum paham secara maksimal terkait hal
tersebut. Yang pada akhirnya pembangunan yang menjadikan sumber daya alam
sebagai penunjang utamanya hanya
berorientasi ekonomi semata. Padahal kalau dilihat dari konsep pembangunan
berkelanjutan sudah menjadi asas dalam berbagai hukum nasional maupun
internasional, namun memperhatikan konsidi lingkungan hidup pada saat ini
sangat memprihatinkan, artinya konsep yang ideal masih jauh terealisasi dalam
fakta di lapangan, oleh karenanya dibutuhkan kesadaran dan kesungguhan dari
segenap elemen bangsa untuk mengamalkannya.
Arah pembangunan yang menjurus pada kerusakan lingkungan dan tatanan sosial
ini berakar pada cara pandang dualistik, baik dalam kebijakan pembangunan
maupun ilmu yang menopangnya. (Oekan, 2017) Lalu kerusakan lingkugan sebagai
mana telah sedikit disinggung, selanjutnya Oekan (2017) mengatakan bahwa
penyebabnya adalah dari sifat kapitalistik manusia yang membutuhkan alat
produksi yang padat untuk sistem perekonomiannya dan umunya ia memerlukan
sumber daya yang senantiasa meningkat untuk menopang keberlangsungannya.
Persoalannya, tiada sumber daya lain, selain sumber daya alam, yang bisa digali
untuk memenuhi kebutuhan perekonomian yang harus selalu tumbuh. Setiap jengkal
muka bumi digali dan setiap sudutnya dikeruk hanya untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Dampaknya sudah kita saksikan, kerusakan lingkungan
dimana-mana. Maka tidak heran ketika Stiglitz (2006) menurutkan bahwa kegagalan
penciptaan stabilitas di sektor lingkungan hidup akan mengakibatkan bencana
yang lebih besar di masa yang akan datang.
Selanjutnya menurut para ahli, pembangunan berkelanjutan dapat memenuhi
kebutuhan kita saat ini, tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan
datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (WCED, 1987). Ada yang menarik dari
gagasan hajer yang mengatakan bahwa gagasan pembangunan berkelanjutan untuk
menghadirkan wacana lingkungan hidup tidak dilihat dari produk, kemajuan, dan
nilai paham hijau. Tetapi lebih kepada perjuangan antara kepentingan politik
yang disuarakan oleh aktor seperti penguasa, akademisi, politisi, aktivis atau
yang lainnya (Hajer, 1995). Karena benar bahwa perjuangan implementasi pembangunan
berkelanjutan terletak pada pemegang kekuasaan, unsur politik dan pemodal yang
berhadapan dengan kelompok pegiat isu
lingkungan.
Oekan (2017) mengutip pendapat Pawloski dan Pearman yang menuturkan bahwa
pembangunan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia ia
diharapkan untuk tidak membahayakan kehidupan makhluk lain dan alamnya. Artinya
seiring dengan meningkatnya kesejahteraan manusia, diharapkan kehidupan makhluk
lainnya dan ekosistemnya serta stabilitasnya terjaga dengan baik.
Di Indonesia dan negara lainnya pembangunan berkelanjutan menjadi agenda
dalam setiap kebijakan pembangunan yang dirumuskan dan dilaksanakan oleh
pemerintah, tetapi secara substansial belum terlaksana sesuai tujuan.
(Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2002). Hal ini bisa terlihat
dari masih banyaknya kerusakan alam dan bencana alam yang terjadi di Indonesia.
Selain tolak ukur yang harus menjadi bahan pertimbangan, faktor-faktor yang
menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan
perlu segera diperbaiki. Banyak faktor yang menyebabkan pembangunan
berkelanjutan di Indonesia selalu menjadi sebuah mimpi. Hal itu bermula dari
masalah yang bersifat filosofis, kepentingan politik, sampai kepada masalah
teknis pelaksanaannya, termasuk sosialisasi pembangunan berkelanjutan itu
sendiri (Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia).
Problematika hari ini adalah perusakan dan pencemaran lingkungan dalam
konstruksi hukum positif belum dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM. Dalam
UU no 39 tahun 1999 dijelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijungjung tinggi,
dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan
serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dalam karya tulisnya Suardi menjelaskan tenatng pelanggaran HAM yang oleh
ia didefinisikan dengan setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk
aparat negara baik disengaja maupun tidak yang secara hukum mengurangi,
menghalangi, dan membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau yang
dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan
memperoleh penyelesaian hukum yang adil
dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
Atas penjelasan tersebut, pelanggaran HAM itu dianggap sebagai pelanggaran
ketika bersentuhan langsung dengan nilai kemanusiaan itu senditi. Oleh karena
itu, memang sedikit agak sulit ketika menganggap pencemaran dan perusakan
lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dikualifikasikan
sebagai pelanggaran HAM, padahal dalam instrumen hukum lainnya termasuk konstitusi mengintegrasikan lingkungan
sebagai bagian dari HAM yang termasuk kedalam HAM generasi III.
KESIMPULAN
Pada bagian kesimpulan, dibagi kepada dua poin, diantatanya
1.
Prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang
mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan
menyerasikan keduanya dalam peb=mbangunan. Dalam pelaksanaannya pembangunan
berkelanjutan menganjurkan dan mewajibkan agar pembangunan dilaksanakan dengan
memperhatikan faktor lingkungan dan daya dukung lingkungan. Namun dalam
implementasinya masih banyak persoalanan, sifat manusia yang serakah
mengakibatkan pemenuhan kebutuhan manusia yang konsumtif melalui pembangunan
dengan cara mengeksploitasi lingkungan secara masif tanpa mempertimbangkan
keselamatan lingkungan hidup dan manusia itu sendiri. Sehingga masih banyak
anggapan yang beredar di masyarakat dan/atau manusia bahwa sumber daya alam itu
adalah materil yang harus dieksploitasi untuk memenuhu kebutuhan manusia. Oleh
karena itu, pengelolaan lingkungan diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya
alam sebagai penyuplai kebutuhan materi semata, inilah penyebab utama penerapan
prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.
2.
Pembangunan berkelanjutan harus terus disosialisasikan supaya pemahaman
semua elemen bisa paham dengan maksimal, selanjutnya tolak ukur dalam
pembangunan berkelanjutan pun harus menjadi syarat wajib dalam pelaksanaanya,
serta faktor-faktor yang menghambat pembangunan berkelanjutan harus segera
diselesaikan oleh semua pihak.
3.
Eksploitasi lingkungan yang dilakukan manusia itu sudah sangat
besar-besaran tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkan terhadap kerusakan
lingkungan itu yang akibatnya lingkungan tidak dapat berfungsi sebagai sistem
pendukung kehidupan yang dalam ekosistem kehidupan manusia dan lingkungan
saling berkaitan. Dengand demikian, apabila terjadi kerusakan dan pencemaran
lingkungan maka kebutuhan manusia untuk keberlangsungan hidupnya pun terganggu
dan bahkan bisa menyebabkan manusia punah. Maka dalam perspektif HAM, lingkungan
dikategorikan sebagai HAM generasi ketiga.
REFERENSI
Abdoelah. S Oekan. 2017. Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan.
Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Hajer, M.A. 1995. The Politics of Environmental Discourse: Ecological
Modernization and The Policy Press. New York: Oxford
Kementrian Lingkungan Hidup, Republik Indonesia. 2002. Dari Krisis
Menuju Keberlanjutan di Indonesia:
Tinjauan Pelaksanaan Agenda 21. Jakarta
Suardi. 2014. Problematika Penerapan Prinsip Sustainable Development
Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan HAM.
Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 8 No 4. Universitas Tadulako.
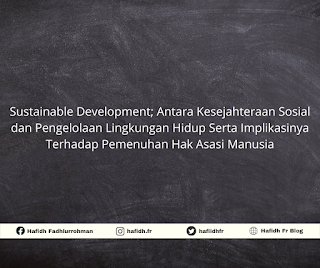

No comments:
Post a Comment